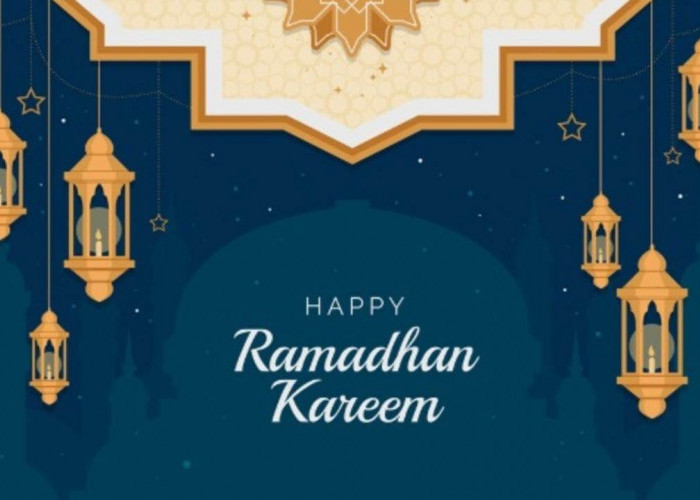Modal History dalam (Re) Aktualisasi Jati Diri Sumatera Selatan: Sebuah Catatan

Oleh: Dr. Dedi Irwanto, M.A.
Dosen FKIP Universitas Sriwijaya
dan Penggiat Sejarah Sumatra Selatan
Siapa kita?
Jati diri berkenaan dengan kata viral saat ini: “Siapa kita? Indonesia”. Maka kalau ditanyakan “Siapa kita? Sumatra Selatan”. Apa jawabannya? Menjadi Sumatra Selatan adalah kebanggaan sekaligus beban. Kenapa? Sumatra Selatan identik dengan Palembang. Dari mana pun daerah asal kita. Jika sudah diluar disebut “Wong Plembang”. Kenapa? Dalam frame historis, Sumatra Selatan “kata baru”, dibandingkan “kata” Palembang yang jauh lebih “tua”. Masa lalu tidak pernah disebut Sumatra Selatan. Sumatra Selatan baru muncul secara resmi sekitar awal sampai pertengahan abad ke-20. Belanda yang memulai penyebutannya. Pernah pada tahun 1931 yang dirintis sejak 1916, Pemerintah Kolonial Belanda berusaha membentuk Provinsi Zuid Sumatra (Sumatra Selatan) menggabungkan daerah Palembang, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Babel. Namun gagal. Sejak awal Sumatra Selatan disebut sebagai Kesultanan Palembang dan Keresidenan Palembang. Artinya, seluruh wilayah Sumatra Selatan disebut Palembang. Oleh sebabnya tak mengherankan, Sumatra Selatan lebih dikenal sebagai Palembang atau Negeri Palembang, budak (anak mudo) Palembang.
Tahun 1946, tepat 15 Mei yang menjadi patokan HUT Sumatra Selatan. Sumatra Selatan dijadikan sub provinsi dibawah Provinsi Sumatra. Sub Provinsi Sumatra Selatan meliputi Keresiden Palembang, Lampung, Bengkulu dan Babel. Pemimpinnya disebut Gubernur Muda, pertama dr. AK Gani (Mei-Agustus 1946), kedua dr. M. Isa (1946-1948), ketiga dr. AK Gani lagi (DMI SS, setelah Agresi II Belanda-17 Des 49), Keempat Kembali lagi ke dr. M. Isa (1949- 17 Agustus 1950, pembentukan Provinsi Sumatra Selatan 15 April 1948 (UU No. 10/48, pemekaran dari Prov. Sumatra, RIS dibubarkan 1950, UU 3/50 (10/Mar/50 Pembentukan Prov. SS -1953), Kelima, Gubernur R. Winarno Danuatmodjo (Des 1953).
Kembali ke narasi kenapa menjadi Sumatra Selatan adalah kebanggaan sekaligus beban? Pertama, kenapa “beban” karena stereotif Wong Plembang selalu bersisi negatif “di luar”, “berdarah panas/mlawan/jagoan”, “identik curanmor”, “tukang rusak anak gadis”, dan lain-lain. Selanjutnya, kenapa harus “bangga” karena stereotif Wong Plembang juga selalu memiliki sisi positif “di luar”, “royal”, “blagak/tampan/cantik”, “parlente/necis”, dan lain-lain. Kenapa ada dua sisi ambigu ini? Sisi positif disebabkan kemakmuran ekonomi yang luar biasa di negeri Palembang. Sisi negatif tidak lepas dari ada dan munculnya berbagai masa transisi di Palembang.
Jati Diri Makmur “Wong Plembang”
Kenapa kita Makmur? Pertama, membayangkan masa lalu Palembang tidak seperti masa kini. Sebelum abad 20. Negeri Palembang terpetakan secara geografis oleh berbagai sungai yang memanjang. Sungai ini satu-satunya sarana transprotasi dan penghubung antar daerah. Sungai membentuk kesatuan suku-suku sebagai landasan wilayah genealogis di Sumatra Selatan. Sungai juga sekaligus pemisah antar wilayah. Sehingga , contohnya di masa itu masyarakat suku Komering di Martapura, tidak mudah berhubungan dengan masyarakat suku Musi di Sekayu. Jadi masyarakat kita, Sumatra Selatan, terpisahkan dan membentuk kesatuan wilayah secara genealogis. Awalnya perkawinan silang (eksogami) antar suku sulit dilakukan. Kita di Sumatra Selatan, mengental di masing-masing suku.
Pada waktu itu, ini keuntungan karena kita mencoba mandiri masing-masing. Membentuk kesatuan otonom terkecil dalam konsep marga. Marga cara kita mengatur diri masing-masing. Marga ini bentuk asli system pemerintah, adat dan budaya di Sumatra Selatan. Kenapa asli, memang pada abad ke-17 istilah ini mengadopsi kata sankrit “varga”. Namun sebelumnya istilah ini identic dengan kata lokal, Melayu kuno, seperti “margga” di dalam prasasti Talang Tuwo, “Marsi-haji” dan “Hulun-haji” dalam prasasti Telaga Batu, atau “gotrasantana” dalam prasasti Kota Kapur. Namun semua mengacu pada makna kesatuan wilayah yang menyerupai marga ini. Kenapa berbeda, kemungkinan karena awalnya penyebutan marga itu tidak tunggal di masing-masing wilayah Sumatra Selatan, seperti marga, kebuwaian, sumbay atau petulai.
Lalu apa untungnya kita hidup mandiri dalam wilayah marga tersebut? Karena muncul ekonomi kemakmuran di masing-masing marga, otonom ini menyebabkan marga menciptakan berbagai kegiatan ekonomi mandiri dan kreatif. Misalnya masyarakat marga diberi hak luas atas tanah, bisa mengelola tanah untuk pertanian ditanami segala rempah dan tanaman substansif (masa prakolonial) dan tanaman komersial macam karet dan sawit (masa kolonial), serta menyangkut kepentingan bersama seperti lebak-lebung, hasil hutan, dll dikelola marga untuk kepentingan masyarakatnya. Perdagangan dan ekonomi uang secara merata tumbuh berkembang di marga. Pergolakan perdagangan di marga-marga uluan bermuara di/ke ibukota, Palembang. Maka Sumatra Selatan muncul sebagai negeri para pedagang.
Setiap kekuasaan besar dibangun atas perdagangan. Hubungan perdagangan dengan luar menyebab munculnya apa yang disebut Hasbullah (1996) dalam buku Mamang dan Belanda: Goresan-goresan Wajah Sosial Ekonomi dan Kenedudukan Sumatera Selatan Zaman Kolonial dan Refeleksinya Hari Ini sebagai “outward looking” (pandangan keluar). Orang asing dihargai, sehingga komunitas Arab, Cina dan Timur Asing serta suku di Nusantara lainnya tentram menetap di Negeri Palembang. sekaligus “inward looking” Ketika berhubungan kedalam, tanpa ada segregasi kesukuan, Negeri Palembang zero conflict. Simbiosis mutualisme muncul antar masyarakat, marga-marga di ulu sebagai sumber komoditas, ilir pemasar komoditas. Kemakmuran Bersama berkembang dalam bentuk “oedjan mas” di seluruh Negeri Palembang. Manusia Palembang bisa muncul dalam bentuk “royal”, “parlente” dan “blagak/cindo nian”. Kelebihan ini dinikmati misal kalau yang kuliah era 1950-1970-an di Yogyakarta dengan stereotif “perusak anak gadis”, pacaran akrab di sana, namun disuruh pulang karena dijodohkan di uluan.
Namun kemakmuran ekonomi ini juga ini memunculkan berbagai masa transisi, terutama di masa kolonial. Pengelana dari masyarakat dusun di marga-marga uluan migrasi permanen ataupun menetap di Kota Palembang. Kebanyakan mereka tanpa skill, bekerja serabutan atau menempu “jalan pintas”, bersisi negatif menjadi “centeng, jagoan” di toko-toko, atau mohon maaf “halusnya mlawan/ngagangi, kasarnya pemalak” di kota.
Karena mereka berbudaya baru, budaya wong kota yang cenderung bebas, karena terlepas dari akarnya aturan marga di dusun-dusun mereka. Stereotif ini makin dipertegas, ketika hapusnya marga di uluan Sumatra Selatan. Perlindungan marga atas hak kepemilikan tanah masyarakat ulu mulai tercerabut. Perusahaan-perusahaan perkebunan (baca PT) banyak yang membeli, kalau tidak “merampas” tanah-tanah mereka. Semakin ke sini, semakin banyak mereka menjadi penganguran dalam dusunnya sendiri. Akibatnya, selain membanjiri Kota Palembang, banyak juga muncul “preman-preman” baru “berbaju” suruhan PT atau pamong desa “berwajah baru” penerbit SKT dan penikmat “proyek” yang semakin jauh dengan simbol kebesaran para proatin, pamong zaman marga.
Saat ini, penguasaan ekonomi bersama dan perdagangan yang menjadi modal historis berimplikasi politis, ekonomi dan sosbud pada masyarakat terdepan, marga semakin menukit turun tajam di uluan. Jika hal ini tidak diperbaiki, maka kita akan semakin kehilangan modal histori ini. Salah satu solusinya, kembalikan sistem marga di Sumatra Selatan. ***
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: